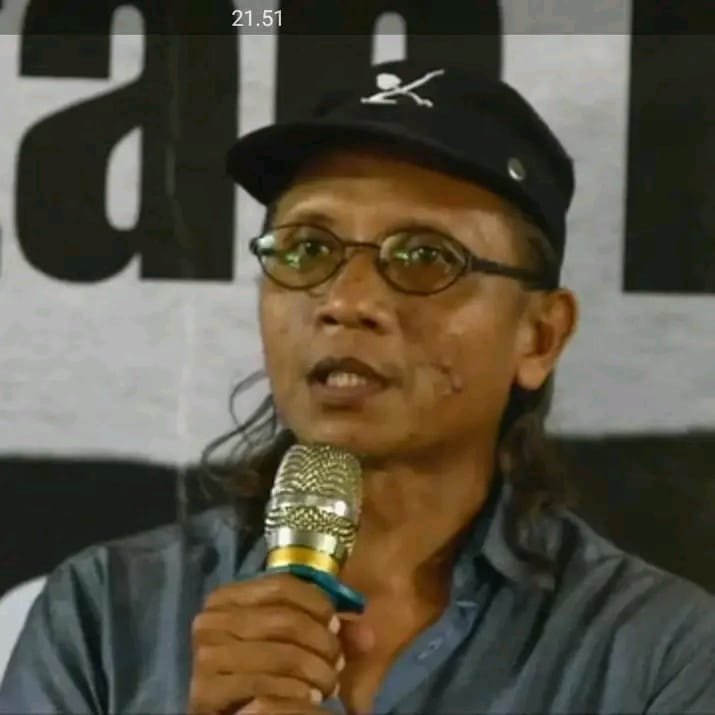RAKYATMERAHPUTIH – Tahun 2025 yang segera berlalu merupakan tahun penuh gejolak bagi Indonesia. Negeri ini diuji oleh serangkaian protes massal terbesar sejak Reformasi 1998, krisis kebijakan, represi aparat, serta bencana alam dahsyat di Pulau Sumatera. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan proyeksi rata-rata 4,8-5% dan inflasi terkendali, ketimpangan sosial-ekonomi tetap menganga, disertai derita rakyat yang tak kunjung mereda. Program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan, sementara banjir bandang dan longsor di akhir tahun menelan ribuan korban jiwa. Di tengah semua itu, muncul #Ereksikebangsaan—kebangkitan kesadaran nasional yang semakin kuat, meski sering terhambat oleh pengawasan ketat, represi, dan retorika penguasa.
Hampir setiap langkah anak bangsa diawasi ketat oleh aparat, sementara suara kritis kerap dibungkam. Pajak yang membebani rakyat sering hilang dalam praktik korupsi atau dialihkan untuk alat represi, seperti gas air mata yang kembali ditembakkan kepada pembayarnya sendiri. Ketimpangan kekayaan semakin lebar: segelintir elite menguasai sumber daya utama, sementara kelas menengah dan bawah berjuang bertahan di tengah tekanan ekonomi. Derita ini bukan sekadar data statistik, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan dalam keseharian—sakit yang tak tergambar dalam grafik, tapi membekas dalam kehidupan individu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijanjikan sebagai terobosan gizi nasional, justru menjadi simbol kegagalan tata kelola. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, ribuan kasus keracunan massal tercatat di berbagai daerah—akibat makanan basi, tidak higienis, atau pengolahan buruk—menyebabkan trauma bagi orang tua dan anak-anak sekolah. Frasa seperti “Anak disekolahkan untuk cerdas, bukan diracuni” mencerminkan kekecewaan publik. Kebijakan “gratis” yang dibiayai pajak rakyat ini lebih banyak menghasilkan pencitraan politik daripada manfaat nyata. Diperlukan evaluasi menyeluruh: penghentian sementara jika perlu, penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian, dan prioritas pada pendidikan berkualitas serta pengawasan ketat untuk program serupa.
Sepanjang tahun, gelombang protes mewarnai negeri: dari gerakan #IndonesiaGelap di awal tahun hingga demonstrasi besar-besaran pada Agustus-September yang menuntut keadilan ekonomi, reformasi aparat, dan anti-korupsi. Aksi ini diresponi represi brutal—belasan tewas, ribuan luka, dan penangkapan massal lebih dari 3.000 orang, termasuk ratusan anak di bawah umur. Yang mengkhawatirkan, kriminalisasi terus berlanjut hingga akhir tahun: aktivis lingkungan seperti Adetya Pramandira (staf WALHI Jawa Tengah) dan Fathul Munif (Aksi Kamisan Semarang), serta puluhan pegiat di Bali, Magelang, dan daerah lain, ditangkap dengan tuduhan hasutan atau UU ITE hanya karena bersuara kritis. Ini mencerminkan penyempitan ruang sipil yang sistematis, di mana demonstrasi damai dikriminalisasi, sementara elite sering kebal hukum.
Di bidang hukum dan keamanan, polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 menjadi sorotan utama. Aturan ini membuka jabatan sipil bagi anggota Polri aktif, meski bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan supremasi sipil. Fenomena ini menandai kemunduran reformasi 1998, dengan nuansa militerisme baru: perluasan peran TNI dan Polri ke ranah sipil. Aparat yang cedera mendapat pangkat istimewa, sementara rakyat—termasuk aktivis yang dikriminalisasi—yang terluka atau kehilangan nyawa saat menyuarakan aspirasi justru menghadapi teror dan pengadilan. Negara memiliki penegak hukum, tapi sering kekurangan penegak keadilan sejati. Reformasi aparat yang dijanjikan terasa hampa.
Isu investasi pertambangan, termasuk rencana tambang emas di Bukit Sanggul, Seluma, Bengkulu, terus menuai penolakan masyarakat. Proyek ini, yang melibatkan pemodal besar, mengancam kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penolakan ini semakin kuat pasca-bencana Sumatera, sebagai pengingat bahwa eksploitasi tanpa kendali dapat memperburuk kerentanan ekologis.
Puncak gejolak terjadi di akhir tahun: banjir bandang dan longsor dahsyat menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga Desember 2025, menewaskan lebih dari 1.100 jiwa (data terakhir BNPB hingga akhir Desember), melukai ribuan, serta mengungsikan ratusan ribu orang. Bencana ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, melainkan konsekuensi degradasi hutan, alih fungsi lahan, dan kelalaian struktural jangka panjang. Jika akar masalah seperti deforestasi untuk tambang dan proyek infrastruktur tak dituntaskan, kekecewaan rakyat—termasuk suara separatisme di daerah terdampak—akan semakin menguat.
Gejolak ini kadang dimanfaatkan elite untuk pertarungan internal, sementara isu substansial rakyat—seperti penghentian kriminalisasi aktivis—belum menjadi prioritas. Penguasa sering menyamarkan realitas dengan retorika manis dan data selektif, sehingga hanya mereka yang kritis yang bisa tetap waspada.
Di penghujung 2025, mari kita renungkan:
- Otoritarianisme berbahaya karena menafikan kecerdasan kolektif rakyat dan menuntut ketundukan buta.
- Harga diri sebuah bangsa terletak pada kemampuan meruntuhkan tirani zalim, bukan hanya melalui amarah destruktif.
- Sekelompok orang baik dengan aturan buruk masih bisa melahirkan kebaikan; sebaliknya, orang jahat dengan aturan baik pun dapat melahirkan kejahatan.
- Aturan saja bukan solusi mutlak—kepemimpinan yang arif dan berpihak pada rakyatlah yang esensial.
Tahun baru 2026 di depan mata. Semoga bukan tahun kegetiran baru, melainkan kebangkitan sejati yang berkelanjutan. Rakyat harus sabar, tapi bukan sabar pasif seperti Fir’aun yang tak memiliki tongkat Nabi Musa untuk membelah lautan ketidakadilan.
EREKSIKEBANGSAAN HARUS TERUS MEMBARA, UNTUK INDONESIA YANG ADIL, BERDAULAT, DAN BERMARTABAT.